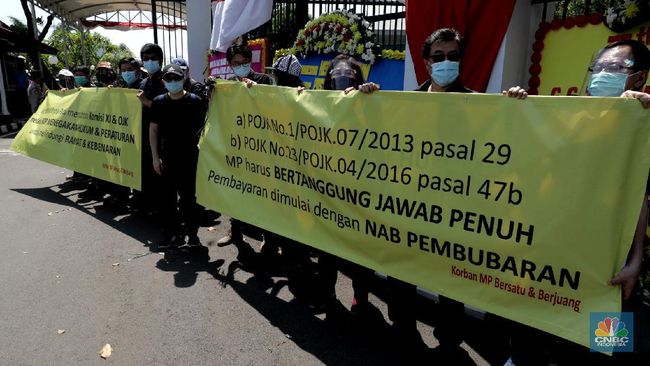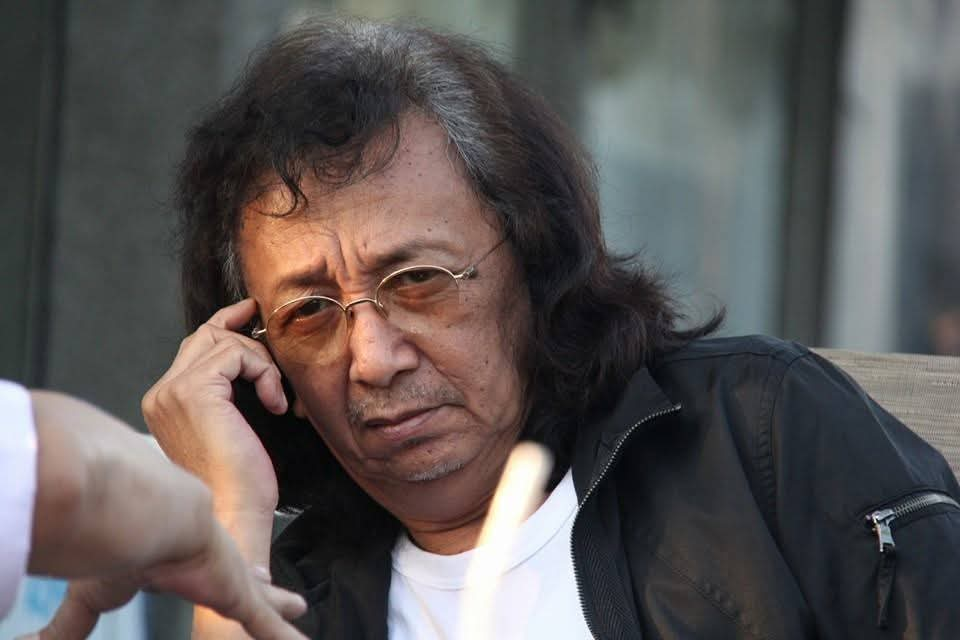Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Berbicara tentang Hari Sumpah Pemuda tidak bisa dilepaskan dari sejarah panjang lahirnya kesadaran kolektif bangsa. Budi Utomo, yang berdiri pada 5 Mei 1908, menjadi tonggak awal gerakan kebangkitan nasional modern.
Meskipun sering disebut sebagai organisasi kaum terpelajar, sejatinya Budi Utomo adalah laboratorium intelektual bangsa, sebuah embrio kesadaran politik dan sosial yang menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan muda. Dari sanalah lahir berbagai organisasi pemuda seperti: Jong Java, Jong Sumatera, Jong Ambon, dan Jong Celebes, yang pada akhirnya berpadu dalam satu simpul historis: Kongres Pemuda II tahun 1928.
Kongres tersebut melahirkan ikrar monumental Sumpah Pemuda, yang hingga kini menjadi DNA ideologis generasi muda Indonesia: "Kami putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia."
Ikrar tersebut bukan sekadar ungkapan simbolik, bunyi dan maknanya yang begitu sakral menjadi kontrak sosial lintas generasi sebagai sebuah komitmen untuk membangun bangsa berdasarkan persatuan, identitas nasional, dan semangat kolaboratif. Semangat itu terus hidup dan menjadi landasan bagi penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) muda Indonesia di era modern.
Kini, hampir seabad setelah ikrar itu dibacakan, tantangan yang dihadapi pemuda bukan lagi penjajahan fisik, melainkan kompetisi global, disrupsi teknologi, dan krisis identitas digital. Pemuda masa kini tidak cukup hanya bersemangat: mereka harus berkompeten, berkarakter, dan berdaya saing global. Gerbang kemerdekaan kini bukan lagi perjuangan melawan penjajah, tetapi perjuangan melawan ketertinggalan, kemiskinan pengetahuan, dan stagnasi moral.
Pemuda Masa Kini
Kalau kita elaborasi dengan kondisi saat ini, saya begitu terpukau dengan penggalan pidato dari Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti yang disampaikan saat pelaksanaan wisuda 1.950 lulusan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) di Medan, Selasa (8/7/2025).
Penggalan yang disampaikan adalah: "Sarjana sejati adalah mereka yang mampu menjadi pemecah masalah (problem solver), bukan hanya penghapal teori atau pemburu gelar. Kita jangan hanya menjadi pengguna teknologi. Kita harus menjadi generasi yang menanamkan nilai-nilai kebersamaan, kearifan, dan persatuan di tengah pesona AI."
Bagi saya pribadi, frasa dalam pidato yaitu: 'problem solver' dan 'bukan hanya pemburu gelar,' sebagaimana yang dijelaskan Mendikdasmen Abdul Mu'ti, tentu begitu merepresentasikan realita generasi bangsa kita, yang saat ini masih tinggal dalam 'seremonialisasi' gelar semata.
Padahal, tugas dari sarjana seharusnya ikut serta berpartisipasi menyelesaikan permasalahan bangsa, termasuk persoalan-persoalan yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pernyataan beliau semakin memberikan angin segar, bahwa pendidikan kita saat ini tidak lagi hanya sekadar di ruang-ruang kampus, namun terjun dan turut hadir berkontribusi di masyarakat lewat kompetensi masing-masing.
Berbicara tentang orang muda Indonesia hari ini, kita tidak dapat hanya melihat dari satu sisi kacamata optimisme. Memang benar, banyak anak muda telah menorehkan prestasi luar biasa, dari ajang sains/akademik di level internasional, olahraga, hingga inovasi digital yang mengharumkan nama bangsa di kancah global.
Namun di balik kisah sukses itu, tersimpan realitas struktural yang kompleks: ketidakpastian ekonomi, fenomena pengangguran terdidik, tingginya angka kriminalitas oleh kalangan muda, serta beragam persoalan sosial dan psikologis yang merefleksikan adanya ketimpangan dalam pembangunan manusia.
Kalau kita melihat data lainnya, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa mayoritas kelas menengah Indonesia saat ini didominasi oleh Generasi Milenial (24,60 persen), disusul oleh Generasi Z (24,12 persen), dan Generasi Alpha (12,77 persen).
Secara demografis, komposisi ini menggambarkan potensi besar bagi kemajuan bangsa karena mereka merupakan tulang punggung produktivitas nasional dan penentu arah ekonomi masa depan. Namun, di balik potensi tersebut, terdapat pertanyaan mendasar: apakah menjadi bagian dari kelas menengah berarti aman dari guncangan ekonomi? (BPS, 2024)
Jawabannya, tentu tidak. Justru kelompok inilah yang paling rentan terhadap fluktuasi ekonomi dan ketidakpastian struktural. Mereka bukan tergolong miskin secara administratif, karena secara pendapatan berada di atas garis kemiskinan. Tetapi secara sosial-ekonomi, kelompok ini sangat rapuh terhadap krisis finansial, kenaikan harga pangan, inflasi biaya hidup, dan ketidakstabilan pekerjaan.
Maka, sebagaimana opini saya di Koran Bisnis Kontan, 5/8/2025: "Orang Muda di Tengah Ketidakpastian Ekonomi," bahwa jeritan orang muda bukan hanya akibat dari dinamika ekonomi global. Ada persoalan mendalam dalam desain struktural kebijakan kita.
Pendidikan tinggi belum selaras dengan kebutuhan industri. Lulusan sarjana membanjiri pasar kerja tanpa keterampilan yang sesuai dengan permintaan. Sementara itu, sektor informal menjadi penampung terbesar, tapi tanpa perlindungan dan kejelasan masa depan.
Asta Cita dan Secercah Harapan
Dalam arah pembangunan nasional lima tahun ke depan, pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dan Asta Cita Pemerintahan Prabowo-Gibran menegaskan perubahan paradigma pembangunan: dari orientasi infrastruktur fisik menuju pembangunan manusia dan sosial.
Hal ini menandai pergeseran penting dari pembangunan berbasis aset menjadi pembangunan berbasis kapabilitas manusia sejalan dengan konsep human capital formation dalam ekonomi pembangunan modern.
Transformasi pembangunan ini diwujudkan melalui berbagai program yang menempatkan SDM muda sebagai pusat kebijakan. Program Makan Bergizi Gratis menjadi bagian dari strategi peningkatan kualitas gizi dan kesehatan generasi muda.
Kemudian Program Magang Nasional yang diinisiasi Kementerian Ketenagakerjaan sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia kerja, merespons fenomena 'skill mismatch' yang menjadi problem struktural pasar tenaga kerja Indonesia, Sekolah Rakyat, beasiswa pendidikan, dan berbagai program prioritas nasional lainnya.
Namun, realisasi Asta Cita tidak cukup berhenti pada tataran program populistik. Diperlukan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang berlandaskan data, riset, dan evaluasi dampak.
Artinya, tantangan terbesar dalam pembangunan SDM muda hari ini adalah tidak lagi melihat kebijakan dari sisi populistik, namun hanya menyasar persoalan struktural. Kebijakan yang hanya menenangkan sentimen publik tanpa memperkuat fondasi produktivitas jangka panjang berisiko menghambat mobilitas sosial dan mengurangi efektivitas fiskal.
Merayakan Pemuda Kita
Jika generasi muda Indonesia hanya dibekali dengan semangat tanpa dukungan sistem yang kokoh, maka mereka akan terus terperangkap dalam siklus bertahan hidup yang berkepanjangan. Kondisi ini tidak hanya menggerus harapan, tetapi juga menumpulkan kapasitas mereka untuk berperan aktif dalam pembangunan nasional. Artinya, kebijakan negara dalam memperkuat daya dukung bagi generasi muda sejatinya adalah menjaga keberlanjutan masa depan republik ini.
Kebijakan negara perlu bertransformasi dari sekadar 'hadir' menjadi benar-benar berpihak. Pendekatan pembangunan sumber daya manusia tidak lagi dapat didasarkan pada indikator administratif semata seperti batas kemiskinan atau tingkat partisipasi kerja, melainkan harus berakar pada realitas sosial-ekonomi yang semakin kompleks dan menuntut intervensi kebijakan yang adaptif, inklusif, dan berbasis data.
Tanpa reformasi sistemik, generasi muda akan terus menghadapi stagnasi sosial-ekonomi yang mengarah pada fenomena "mati segan, hidup tak mau" sebuah kondisi disfungsional akibat lemahnya tata kelola pembangunan manusia.
Tinggalkan Seremonialisasi Belaka
Selama ini, kebijakan kepemudaan di Indonesia terlalu sering terjebak dalam ruang romantisasi menjadikan pemuda sekadar slogan dan simbol perubahan, bukan sebagai subjek pembangunan yang sesungguhnya.
Padahal, dalam konteks pembangunan nasional yang berorientasi pada keunggulan sumber daya manusia, pemuda bukan hanya penerima manfaat, melainkan aktor penggerak transformasi sosial, ekonomi, dan politik. Artinya, sudah saatnya beralih kepada kebijakan yang tidak sekadar 'gimmick,' dan tidak pula berhenti di panggung seremonial atau narasi motivasional yang hampa data.
Tantangan utama kebijakan kepemudaan saat ini adalah fragmentasi antar sektor dan tumpang tindih program. Banyak program lintas kementerian yang berjalan sendiri-sendiri tanpa policy coherence, sehingga tidak menciptakan efek sinergi.
Pemerintah pusat perlu mendesain grand design kebijakan kepemudaan nasional yang terintegrasi dengan RPJPN 2025-2045 dan agenda Indonesia Emas. Dokumen ini harus bersifat operasional dan data-driven, bukan hanya retorika dalam naskah RPJMN.
Kinerja birokrasi sering kali diukur dari serapan anggaran, bukan dari outcome kebijakan. Padahal, dalam konteks kebijakan kepemudaan, yang diperlukan adalah serapan anggaran yang bermakna yakni penggunaan sumber daya yang menghasilkan dampak sosial terukur.Kita tidak lagi membutuhkan kebijakan yang sekadar menginspirasi, tetapi kebijakan yang menggerakkan.
Pemuda bukan alat legitimasi politik atau ornamen pembangunan, melainkan modal sosial strategis bagi keberlanjutan bangsa. Pemerintah pusat harus berani meninggalkan logika seremonial dan menggantinya dengan logika kebijakan berbasis capaian. Intervensi kebijakan kepemudaan yang efektif adalah yang menguatkan kapasitas pemuda untuk memimpin perubahan di ruang sosial, ekonomi, ruang digital, hingga sektor strategis lainnya.
Peringatan Hari Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 2025 harus menjadi momentum reflektif bagi pemerintah untuk menegaskan kembali komitmen terhadap Asta Cita dan visi Indonesia Emas 2045. Kedua agenda tersebut hanya dapat terwujud apabila generasi muda diberdayakan sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan.
Dalam kerangka visi Indonesia Emas 2045, penguatan SDM muda menjadi penentu apakah bonus demografi akan menjadi berkah atau kutukan. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan bahwa semangat Asta Cita bukan hanya slogan, tetapi diterjemahkan ke dalam kebijakan lintas sektor yang saling menguatkan.
Seperti yang dikemukakan oleh Bambang Brodjonegoro, mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, transformasi Indonesia menuju negara maju mensyaratkan dominasi kelas menengah yang tangguh baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Kelas menengah yang adalah orang muda diharapkan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi melalui daya beli yang berkelanjutan, perilaku konsumsi yang produktif, dan keterlibatan aktif dalam pembangunan nasional.
Namun demikian, cita-cita tersebut semakin sulit dicapai apabila negara belum sepenuhnya menciptakan ekosistem kebijakan yang benar-benar mendukung mobilitas sosial, inovasi, dan kesempatan yang setara bagi seluruh generasi muda Indonesia.
(miq/miq)

 3 months ago
32
3 months ago
32