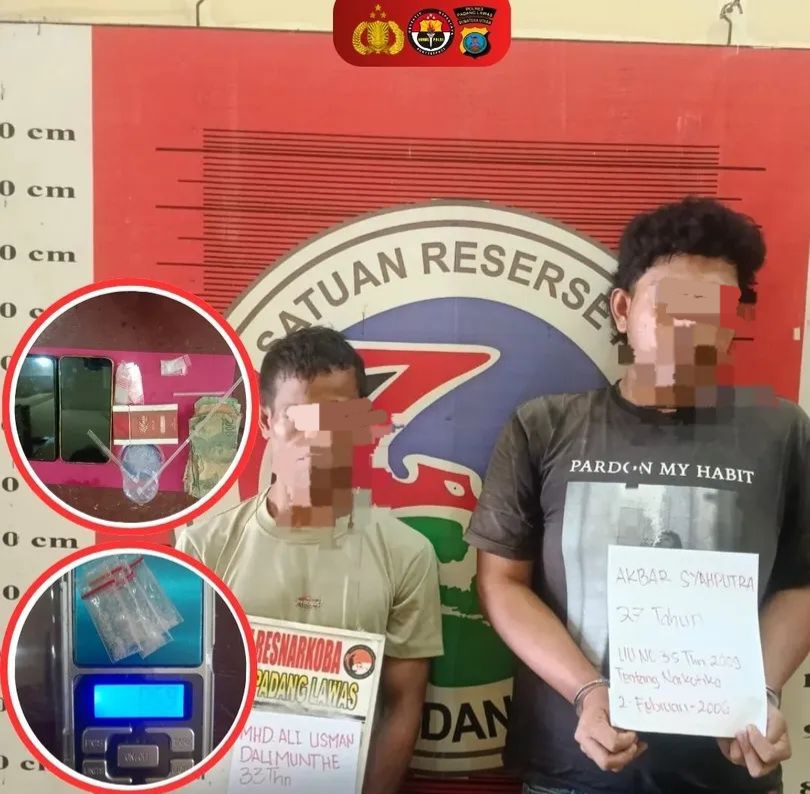Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Keadilan kita seperti timbangan patah: makin besar kejahatan, makin ringan hukuman—asal pelakunya kaya.
Di Medan, kasus seekor ayam bisa lebih menggetarkan tangan jaksa dibanding pencurian miliaran rupiah uang rakyat. Pencuri ayam digelandang dengan borgol, dipertontonkan seolah simbol kejahatan moral, lalu dijatuhi hukuman berbulan-bulan—kadang bertahun—atas nama ketertiban.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Sebaliknya, pejabat atau pengusaha yang menggerogoti hak hidup ribuan orang, merusak pelayanan publik, dan mengubah negara menjadi mesin perampokan, cukup duduk manis di ruang sidang, menunduk sopan, lalu pulang dengan tuntutan yang tak sebanding bahkan dengan harga jam tangannya.
Hukum kita punya keberanian—tetapi kecil, selektif, dan sengaja diarahkan ke mereka yang tidak punya kuasa. Semakin besar kejahatan, semakin tebal tamengnya; semakin sedikit harta, semakin telanjang hukuman itu jatuh.
Tuntutan terhadap Direktur Utama PT Dalihan Na Tolu Grup, Muhammad Akhirun Piliang (H. Kirun), dan anaknya, Rayhan, adalah wajah telanjang kebobrokan jaksa. Dalam sidang Tipikor Medan, Rabu (5/11/2025), Jaksa KPK hanya menuntut H. Kirun 3 tahun penjara dan Rayhan 2 tahun 6 bulan dalam perkara suap proyek jalan Dinas PUPR Sumut senilai Rp4 miliar, dengan nilai proyek ratusan miliar.
“Angka sekecil itu sulit disebut hukuman setimpal,” ujar mantan anggota KY, Farid Wajdi. Tepat. Sebab korupsi bukan cuma soal mengambil uang negara. Ia adalah kejahatan struktural: meruntuhkan kepercayaan publik, menunda pembangunan, memperpanjang kemiskinan, dan merusak masa depan orang banyak. Namun tuntutan itu disengaja tampak jinak. Dingin. Tanpa kegelisahan moral.
Bandingkan itu dengan nasib pencuri ayam di kampung. Jika ia memasuki pekarangan orang pada malam hari, atau bersama satu orang lain, ia dapat dijerat Pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan: ancaman hukumannya 7 hingga 9 tahun penjara. Padahal nilai barangnya tak sampai Rp200 ribu. Bahkan tak sebanding dari harga makan siang para pejabat yang mengucap “pemberantasan korupsi” dengan penuh wibawa di podium-podium acara seremonial.
Di sini, keadilan bekerja seperti timbangan patah: semakin berat beban kejahatannya, semakin ringan hukuman yang dijatuhkan—selama pelakunya kaya, terhubung, atau berada dalam jejaring kekuasaan. Sementara mereka yang miskin, yang bertikai dengan nasib sehari-hari, akan merasakan kerasnya genggaman hukum tanpa cela.
Kita sampai pada pertanyaan krusial: Apakah negara ini benar-benar memandang korupsi sebagai kejahatan serius? Atau sekadar menghukumnya sebagai formalitas, demi menjaga muka, bukan demi menegakkan keadilan?
Lembaga penegak hukum berdalih pada prosedur, pembuktian, dan tafsir undang-undang. Tetapi publik telah lama memahami bahwa perkara korupsi bukan hanya soal teks hukum, melainkan keberanian moral negara dalam memutus mata rantai patronase kekuasaan. Ketika keberanian itu tidak ada, penindakan korupsi hanya menjadi lakon teater penuh drama: ramai, bising, tetapi tak menyentuh akar.
Sementara itu, rakyat kecil tetap menjadi korban paling mudah dari “penegakan hukum”. Mereka dihukum bukan karena besarnya nilai yang dicuri, tetapi karena kecilnya posisi sosial yang diduduki; lemah dan miskin.
Penegak hukum di negeri ini rata-rata memalukan: ingin selamat dari jerat hukum? Jangan mencuri ayam—curilah uang negara sebanyak mungkin. Karena ganjarannya tak setara: paling-paling dua atau tiga tahun penjara, lalu bebas dengan kantong penuh dan kepala tegak. Sementara para pelindungnya—jaksa oportunis, hakim yang jual nama—berkedip santai di balik toga, menukar keadilan dengan privilege tanpa wajah dosa di ruang sidang yang katanya “suci”.
Korupsi berubah jadi jalan pintas paling menguntungkan; penegakan hukum tak lebih dari panggung sandiwara. Orang Medan menyebut tuntutan Haji Kirun dan anaknya “lawak-lawak”—hukuman yang dibuat hanya untuk mengecoh mata publik.
Sementara rakyat, para maling ayam yang dihukum tanpa ampun, hanya bisa melongo ironi: harapan mereka tercabik, harga diri diinjak. Karena di Medan, nirpidana bukan penyimpangan. Ia telah menjadi aturan main, menjadi ladang transaksi bagi para penegak hukum yang bersedia melelang keadilan kepada siapa saja yang membawa cukup uang, bukan seekor ayam jantan, apalagi “ayam sayur”.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.