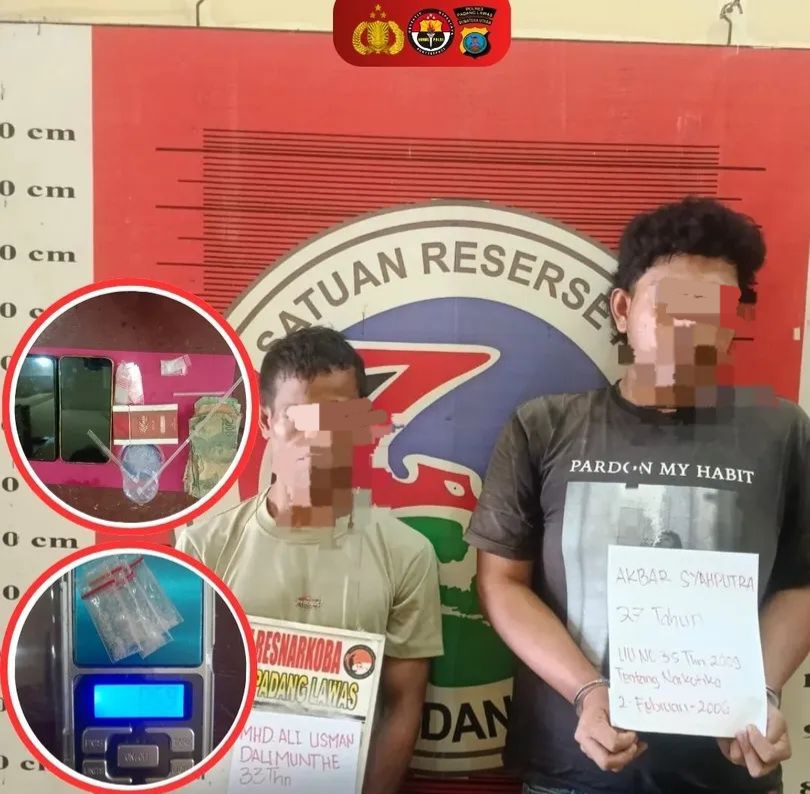Oleh: Marzuki
Pelayanan publik adalah tolok ukur paling jujur dari sebuah pemerintahan. Ia tidak diukur dari pidato seremonial atau inspeksi mendadak (sidak) yang diliput media, melainkan dari pengalaman warga pada titik terlemah mereka. Di Kabupaten Aceh Utara, potret buram dari runtuhnya kontrak sosial ini terekam jelas, bukan di kantor bupati, melainkan di Pengadilan Negeri Lhoksukon.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Pada 14 Januari 2025, seorang warga bernama Abu Bakar (Perkara No. 28/Pdt.P/2025/PN Lsk) terpaksa menempuh jalur hukum. Ia tidak sedang bersengketa tanah. Ia menuntut hak dasarnya yaitu perbaikan akta kematian mendiang istrinya, yang tanggal wafatnya salah diinput oleh instansi berwenang. Kesalahan fatal satu hari (2 Des 2024 diubah menjadi 1 Des 2024) berakibat klaim Jaminan Kematian (JKM) BPJS-TK tertolak.
Yang paling memilukan, Abu Bakar secara eksplisit menyatakan kesalahan ini terjadi “lantaran ditangani oleh calo di Dinas Capil Aceh Utara”.
Ini bukan sekadar maladministrasi. Ini adalah puncak gunung es dari kegagalan sistemik. Seorang warga yang tengah berduka tidak hanya gagal mendapat layanan, tetapi juga dirugikan secara material, dan ironisnya, harus menuntut negara—yang seharusnya melindunginya—untuk memperbaiki data yang dirusak oleh sistem itu sendiri.
Retorika “Governance by Press Release”
Kasus Abu Bakar terjadi di tengah gencarnya promosi “pelayanan prima” oleh pejabat Pemkab Aceh Utara merupakan sebuah jurang antara narasi dan kenyataan.
26 Desember 2024, Kepala Disdukcapil Safrizal menyatakan bahwa pengurusan akta “sepenuhnya gratis” dan “selesai dalam satu hari.” Ia bahkan meminta warga melapor bila ada pungutan liar.
Beberapa bulan kemudian, 19 Juni 2025, Bupati H. Ismail A. Jalil melakukan sidak ke Disdukcapil, menegaskan komitmen terhadap layanan cepat dan bebas pungli.
Kasus Abu Bakar adalah tamparan keras bagi retorika ini. Sistem tidak hanya gagal memberantas calo tapi sistem ini telah membiarkan calo beroperasi begitu bebas hingga memiliki kapasitas untuk memanipulasi dan merusak integritas data vital kependudukan. Janji “laporkan” menjadi lelucon pahit ketika warga justru harus melapor ke pengadilan.
Ini adalah “governance by press release”—sebuah tata kelola pemerintahan yang tampaknya hanya ada dalam rilis media, sementara warganya terperosok dalam labirin birokrasi yang predatoris. Pola ini kronis. Ombudsman RI Perwakilan Aceh telah berulang kali memberi peringatan, dari tahun 2021, 2022, hingga 2024, tentang banyaknya keluhan pelayanan publik. Kegagalan ini, oleh karena itu, bukanlah karena ketidaktahuan, melainkan karena kelambanan birokrasi dan ketiadaan kemauan politik.
Tiga Pilar Kegagalan Desain
Tiga keluhan klasik warga—jarak yang jauh, proses yang lama, dan maraknya calo—sebenarnya bersumber dari satu penyakit kronis yaitu kegagalan desain struktural layanan publik.
1. Tirani Jarak.
Aceh Utara memiliki 27 kecamatan, tetapi seluruh layanan vital seperti KTP, KK, dan akta dipusatkan di Lhoksukon. Kebijakan ini menciptakan “tirani jarak” yang menindas warga di wilayah seperti Sawang, Pirak Timu, dan Langkahan. Untuk sekadar memperbaiki data kependudukan, mereka harus menempuh perjalanan puluhan kilometer, mengeluarkan ongkos besar, dan meninggalkan pekerjaan harian. Kondisi inilah yang membuka ruang bagi calo untuk menawarkan jasa dengan imbalan uang — menggantikan fungsi negara yang absen di wilayah pinggiran.
2. Opasitas Birokrasi.
Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Layanan (SLA) yang transparan adalah akar dari ketidakpastian layanan. Situs online “Layonacut” hanya memuat syarat administrasi, tetapi tidak pernah mencantumkan janji waktu penyelesaian. Ketidakpastian ini menciptakan ruang bagi praktik informal yang menguntungkan calo dan merugikan warga.
3. Ekosistem Calo.
Calo muncul bukan karena warga malas atau curang, melainkan karena sistem yang lamban dan buram. Mereka menawarkan dua hal yang gagal diberikan negara: kepastian waktu dan efisiensi biaya. Dalam kasus Abu Bakar, calo bahkan punya kuasa untuk mengubah data resmi negara—sebuah indikasi bahwa mereka bukan sekadar perantara, tapi sudah menembus sistem dari dalam.
Program “jemput bola” yang sesekali dilakukan di kecamatan seperti Cot Girek (23 Oktober 2024) hanya memperlihatkan paradoks. Ia dipuji sebagai inovasi, padahal hakikatnya adalah pengakuan diam-diam bahwa model sentralisasi di Lhoksukon telah gagal total.
Ilusi Digital dan Krisis Infrastruktur
Ketika kritik datang, jawaban birokrasi selalu sama yaitu digitalisasi. Namun di Aceh Utara, digitalisasi hanyalah ilusi administratif yang menabrak dua tembok keras: tata kelola digital yang buruk dan infrastruktur dasar yang timpang.
Pertama, kegagalan tata kelola digital. Data resmi KemenPAN-RB tahun 2023 menunjukkan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Aceh Utara hanya 1,70 (predikat “Kurang”)—salah satu yang terendah di Aceh. Sebagai pembanding, Aceh Timur meraih 2,30 (“Cukup”), sementara Pemerintah Provinsi Aceh sudah mencapai 3,62 (“Sangat Baik”). Dengan angka seburuk ini, wajar jika portal layanan online hanya menjadi etalase tanpa fungsi.
Kedua, ketiadaan infrastruktur dasar. Digitalisasi tanpa jaringan adalah lelucon. Hingga pertengahan 2025, warga di delapan kecamatan seperti Langkahan, Pirak Timu, Sawang, dan Paya Bakong masih mengeluhkan lemahnya sinyal. Ketua DPRK Aceh Utara bahkan mengakui, “di sejumlah gampong, menghubungi lewat handphone jadul saja sulit.” Bagaimana mungkin mendorong “layanan online” bila warga untuk memanggil ambulans saja harus mencari titik sinyal di tengah sawah?
Meniru yang Sukses
Solusi sebenarnya tidak sulit. Kabupaten lain sudah membuktikan bahwa perbaikan pelayanan publik bisa dilakukan tanpa biaya besar, asalkan ada kemauan politik.
Kabupaten Bengkalis dan Pekanbaru telah membentuk UPTD Dukcapil di setiap kecamatan. Hasilnya, biaya warga turun, calo hilang, dan kepercayaan publik meningkat.
Model Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang diterapkan di Bandung dan Serdang Bedagai juga berhasil mempercepat proses pelayanan.
Contoh paling inspiratif datang dari Kabupaten Sleman dengan inovasi LUKADESI (Layanan Keluarga Berduka Desa Siaga). Ketika ada warga meninggal, aparat desa langsung mengurus akta kematian dan menyerahkannya ke rumah duka sebelum jenazah dimakamkan.
Di sana, negara hadir dengan empati. Sementara di Aceh Utara, warga berduka malah harus menggugat negara karena datanya salah diinput.
Krisis Desain, Bukan Krisis Dana
Kasus Abu Bakar membuka mata bahwa krisis pelayanan publik di Aceh Utara bukan disebabkan kurangnya uang atau teknologi, tetapi kegagalan desain, lemahnya pengawasan, dan hilangnya empati. Pemerintah memiliki anggaran, ASN yang cukup, dan perangkat lengkap—namun sistemnya lumpuh karena tidak ada keberanian untuk berubah.
Langkah darurat yang perlu segera diambil antara lain:
1. Melakukan audit independen terhadap jaringan calo dan oknum internal Dukcapil.
2. Mempublikasikan SOP dan standar waktu layanan yang mengikat secara hukum.
3. Mendesentralisasi pelayanan ke tingkat kecamatan dengan dukungan anggaran memadai.
Reformasi pelayanan publik bukan soal pencitraan, tapi tentang keadilan administratif dan martabat warga. Saatnya Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berhenti mengurus siaran pers, dan mulai sungguh-sungguh mengurus rakyatnya.
Penulis adalah Insinyur dan Pemerhati Kebijakan Publik
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.