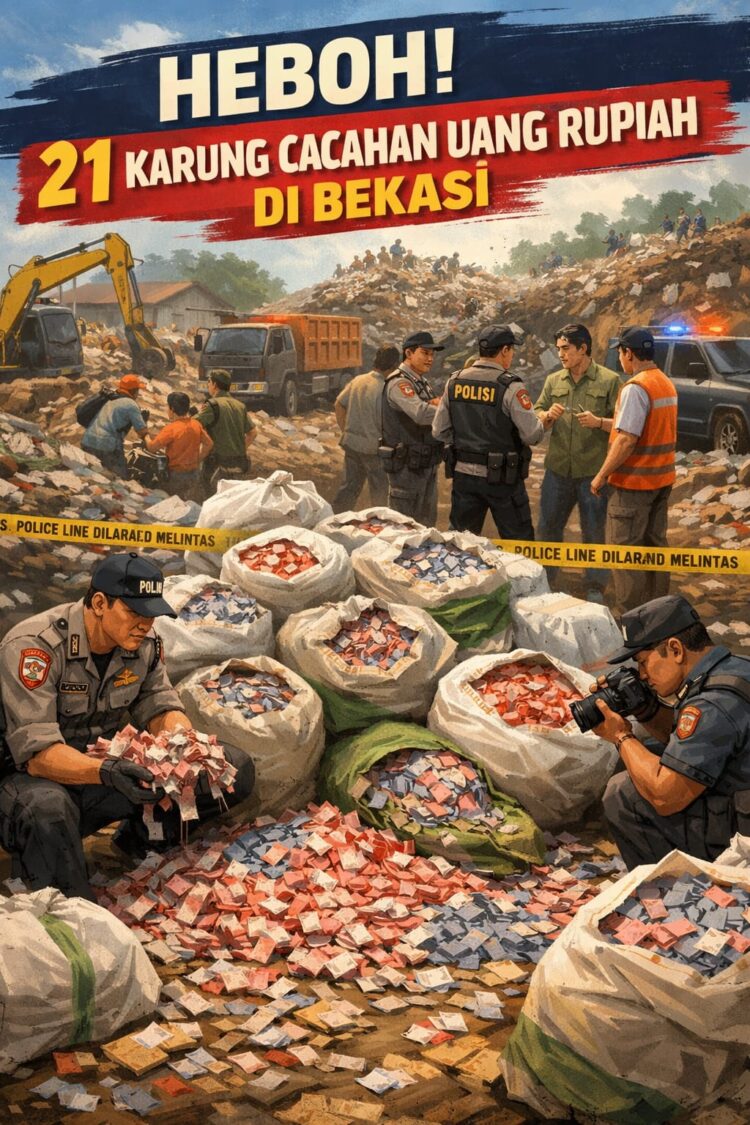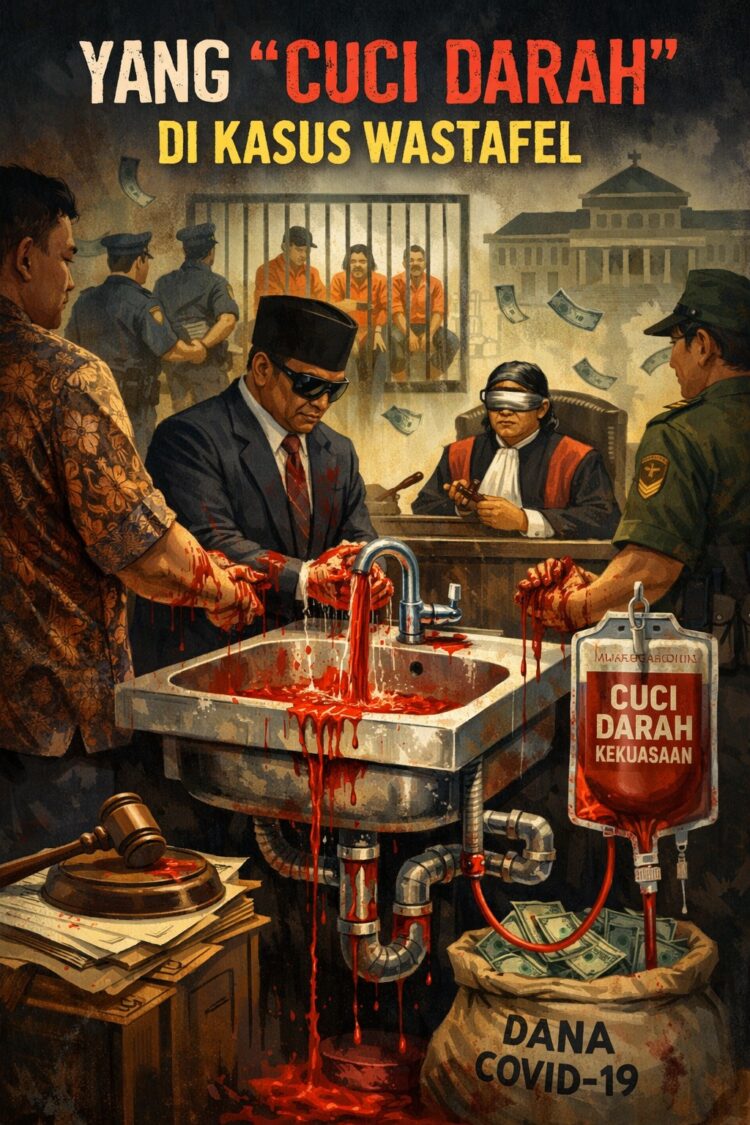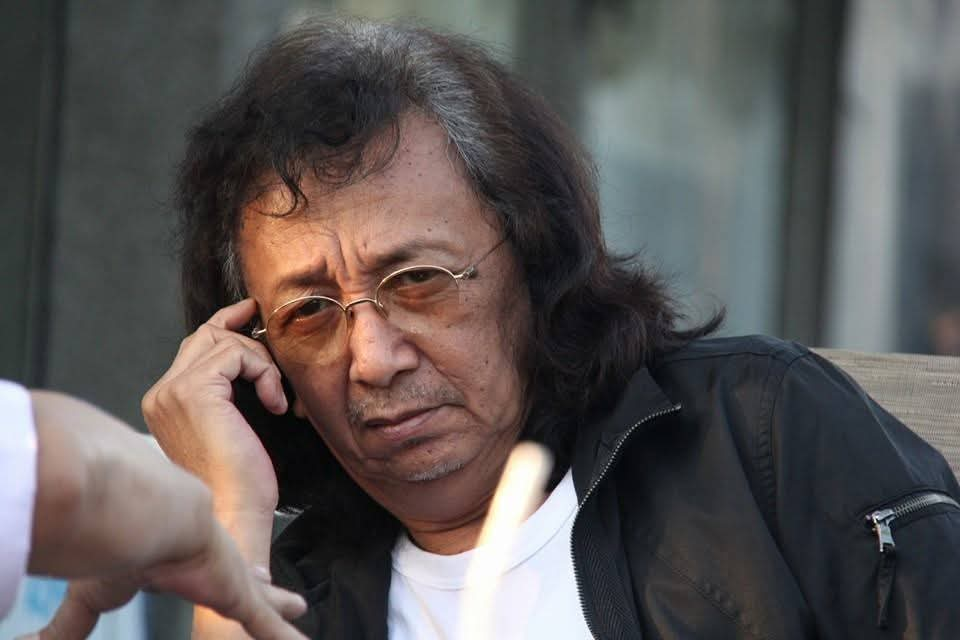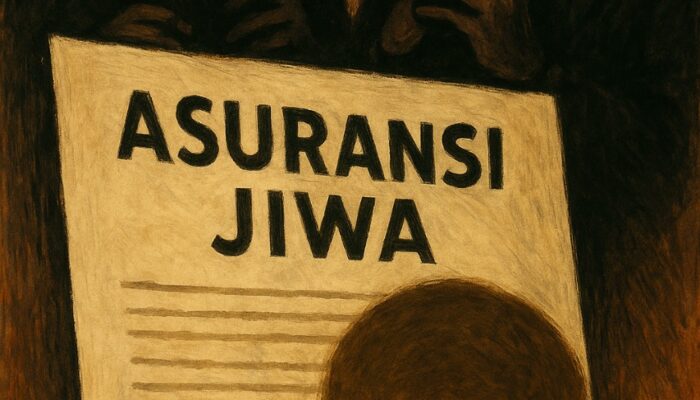
Ukuran Font
Kecil Besar
14px
Aparat penegak hukum—bukan hanya tidak boleh lalai, melainkan juga haram menumpang keuntungan apa pun dari tragedi ini.
Mereka menyebutnya “perlindungan”. Tapi di banyak sudut negeri, polis justru menjelma pagar rapuh yang bisa didorong siapa saja yang berniat menggadai nyawa. Kasus-kasus terbaru menunjukkan betapa mudahnya motif uang menyaru sebagai musibah.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Di Deli Serdang, kematian seorang remaja bernama Ripin alian Achien—mula-mula disebut kecelakaan—bergegas berubah jadi dugaan pembunuhan bermotif klaim asuransi. Keluarga menuding bibi korban terlibat; polisi memeriksa saksi-saksi, perkara berjalan—publik menunggu jawab akhir penyidikan. Pada Senin malam, 27 Oktober 2025, setelah bergulir rumit selama enam bulan, fakta baru polisi menetapkan Juwita alias Bibi dan Kelvin, anaknya, sebagai dalang pembunuhan Ripin, keponakan kandung Juwita. Mereka pun—untuk kepentingan penyidikan—dijebloskan ke sel Mapolresta Deli Serdang. Ini setidaknya menegaskan satu hal: narasi “takdir”, sebelumnya, bisa disusun seperti laporan klaim, rapi tapi menipu.
Lebih gamblang di Medan: notaris sekaligus dosen, Tiromsi Sitanggang, divonis karena merencanakan pembunuhan suaminya. Motifnya? Dugaan klaim asuransi jiwa setengah miliar rupiah. Hukuman di tingkat banding bahkan diperberat jadi 20 tahun penjara. Bahwa profesi terdidik pun terseret menunjukkan lubang pengawasan tak memandang status sosial.
Ironi lain: ketika industri asuransi tumbuh, lubang moral hazard ikut melebar. Premi industri 2024 menembus Rp519,33 triliun; penetrasi memang baru ~2,8–2,84 persen, tapi nilainya cukup menggiurkan bagi siapa pun yang melihat jiwa manusia sebagai komoditas. Ini pasar lindung nilai yang, tanpa partisi etika dan sistem, dapat berubah jadi “pasar gelap” tragedi.
Industri bukannya tanpa pembatas. Hampir semua polis memuat pengecualian: bunuh diri dalam periode tertentu, kematian saat melakukan tindak pidana, dan sebagainya. Namun pagar kertas tak akan menghalangi akal bulus yang menabrakkan skenario “kecelakaan” dengan rencana yang matang. Kerap kali perusahaan baru curiga setelah pola berulang—tertanggung mendadak “celaka”, keluarga tergesa dikremasi, ahli waris terburu-buru mengajukan klaim. Di sinilah investigasi klaim, profil risiko, serta koordinasi dengan aparat menjadi urat nadi pencegahan.
Masalahnya, kita masih longgar dalam dua hal. Pertama, verifikasi forensik. Tidak ada kewajiban nasional yang tegas untuk autopsi pada kematian mendadak tertanggung polis jiwa bernilai besar—padahal ini standar nalar untuk mencegah “musibah rekayasa”. Kedua, pertukaran data. Perusahaan kerap bekerja sendiri-sendiri; OJK memang menata standar, menindak pelanggaran administratif, dan mendorong transparansi produk, tapi repositori intelijen antifraud lintas perusahaan dan akses cepat ke data penegak hukum belum sekuat kebutuhan lapangan.
Belajar dari perkara yang telah berproses hukum, pelajaran kita jelas dan terang benderang. Pertama, wajibkan “red flag protocol”: setiap klaim jiwa di atas ambang tertentu otomatis memicu audit forensik independen, melibatkan dokter forensik dan kepolisian. Kedua, terapkan “beneficiary transparency”—penerima manfaat harus diverifikasi relasinya, rekam jejak finansialnya, dan kemungkinan konflik kepentingannya terhadap tertanggung. Ketiga, bentuk pusat data antifraud industri di bawah koordinasi OJK—bukan melulu soal statistik produksi-premi, melainkan basis anomali: pola polis beruntun pada keluarga inti, perubahan penerima manfaat mendadak, hingga jejak kilat kremasi. Keempat, dorong pengadilan menjatuhkan pidana maksimal pada pembunuhan bermotif klaim—Vonis Tiromsi adalah sinyal, namun harus konsisten agar efek jera terasa memukul.
Kita juga perlu menatap lanskap sosialnya. Ketika ekonomi tersengal, skema “uang instan” kerap menjadi jaring yang menjerat nurani. Kasus kematian Ripin, berikut empat kematian sebelumnya, menunjukkan bagaimana satu orang dalam lingkar keluarga bisa begitu leluasa menghabisi nyawa satu per satu, pada waktu yang ia rasa paling tepat, lalu menukarnya dengan klaim asuransi bernilai miliaran rupiah.
Dalam situasi seperti ini, negara—melalui aparat penegak hukum—bukan hanya tidak boleh lalai, tetapi juga haram menumpang keuntungan apa pun dari tragedi ini. Tugas negara adalah hadir secara penuh, melindungi keluarga yang rapuh, mencegah mereka menjadi “ternak” bagi penjahat yang memelintir instrumen asuransi menjadi mesin pembunuhan berantai.
Pada akhirnya, asuransi adalah janji: menukar ketidakpastian dengan kepastian. Ketika janji itu dipakai menutup jejak kejahatan, kita bukan hanya kehilangan nyawa—kita kehilangan kepercayaan publik. Dan tanpa kepercayaan, industri ini akan merunduk, menyisakan para oportunis sebagai pemenang tunggal. Maka, jangan biarkan polis menjadi tiket masuk ke ruang gelap. Negara, industri, dan kita semua berutang pada para korban untuk memastikan ke depan: tak ada lagi nyawa yang dihitung dengan kurs klaim asuransi.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.