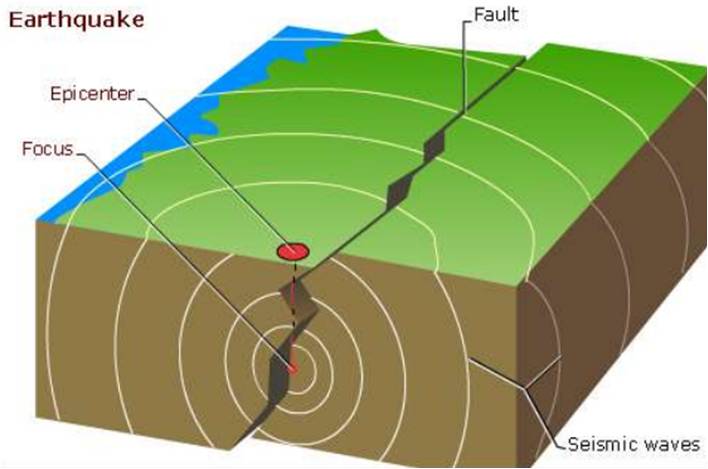Ukuran Font
Kecil Besar
14px
“Jangan hanya melihat memenuhi unsur atau tidak, tapi lihatlah konteks kejahatannya.” | Kompolnas di kasus Hogi Minaya.
TANGIS HISTERIS di Ruang Sat Reskrim Polrestabes Medan, beberapa waktu lalu, bukan hanya drama keluarga. Itu adalah jeritan keadilan yang tercekik. PPS dan LS, dua bersaudara pemilik toko ponsel, ditetapkan tersangka penganiayaan setelah menangkap dua pencuri barang dagangan mereka. Ironisnya, mereka mengamankan pelaku dan menyerahkannya ke Polsek Pancurbatu, kini justru berstatus tersangka—sementara pencuri itu telah divonis 2 tahun 6 bulan penjara.
Pembalikan posisi hukum yang penuh absurditas ini bukan kasus tunggal. Di Sleman, Hogi Minaya, 43, ditetapkan tersangka setelah mengejar penjambret yang merampas tas istrinya. Dua pelaku tewas dalam kecelakaan saat dikejar, dan Hogi dijerat Pasal 310 UU LLAJ dengan ancaman 6 tahun penjara. Baru setelah protes publik meluas dan mediasi restorative justice, Kejari Sleman melepas gelang GPS-nya pada Januari 2026. Di Lombok Tengah 2022, Amaq Sinta, 34, menewaskan dua begal yang menyerangnya, lalu ditetapkan tersangka—baru dibebaskan setelah SP3 diterbitkan.
Polisi selalu punya klarifikasi: “Itu tiga perkara berbeda.” Pencurian di toko, penganiayaan di hotel, kepemilikan senjata tajam. Mereka membedah kronologi dengan presisi forensik, menyebut PPS dan LS melakukan penjambakan, pemitingan, penarikan paksa. Tapi mereka bungkam soal konteks: bagaimana seorang korban pencurian bisa tenang saat pelaku kabur? Bagaimana adrenaline pertahanan diri bisa diukur dengan mistar pasal pidana?
Yang lebih memprihatinkan adalah dugaan praktik tak manusiawi. Ibunda PPS mengeluh anaknya ditahan dalam kondisi sakit, keluarga dilarang membesuk, dan ada permintaan uang Rp3 juta untuk “kamar” di ruang tahanan. Jika benar, ini bukan hanya penyimpangan prosedur, melainkan bisnis dalam penjara. Polrestabes Medan segera menggelar konferensi pers, memaparkan visum et repertum luka memar dan lecet pada para pencuri. Tapi mereka tak menjelaskan mengapa keluarga korban harus berteriak histeris dan berguling-guling di lantai untuk didengar.
Ahli pidana Prof. Alvi Syahrin menegaskan unsur penganiayaan telah terpenuhi. Tapi dia lupa: hukum bukan hanya soal unsur pasal, malainkan soal keadilan substansial. Kompolnas sendiri mengkritik kasus Hogi Minaya: “Jangan hanya melihat memenuhi unsur atau tidak, tapi lihatlah konteks kejahatannya.” Ketika korban dijadikan tersangka, yang terjadi adalah kriminalisasi pembelaan diri—sebuah sinyal berbahaya bagi masyarakat: “Biarkan saja pelaku kabur, nanti kalau mereka tewas, kamu yang dipenjara.”
Di Amerika Serikat, korban kekerasan rumah tangga sering ditangkap karena mandatory arrest law yang memaksa polisi menahan salah satu pihak. Di Colorado, Ellen—seorang ibu yang melarikan diri dari suami pembunuh—justru diborgol karena polisi melihat goresan di leher suami yang dia buat sendiri untuk menjebak. Anak-anaknya dipaksa kembali ke ayah mereka sementara Ellen ditahan semalaman. “Setiap tahun kami menangani setidaknya satu korban yang ditangkap sebagai pelaku,” kata Kristiana Huitron dari Voces Unidosfor Justice.
Bedanya, di sana ada advokat yang memperjuangkan, ada mekanisme pengadilan yang mengoreksi kesalahan polisi. Di Indonesia, korban sering terjebak dalam birokrasi membingungkan dan stigma menghancurkan. PPS ditahan, LS jadi DPO, sementara pencuri sudah menjalani vonis. Sistem hukum kita seperti mesin yang “memakan korban” dan “memuntahkan pelaku”.
Kakak PPS yang berteriak histeris di Polrestabes Medan bukan gila. Dia adalah produk dari sistem yang memaksa rakyat memilih: diam dan jadi korban, atau bertindak dan jadi tersangka. Ketika kepolisian lebih sibuk mencari-cari peristiwa pidana pada korban daripada melindungi mereka, lalu apa bedanya penegak hukum dengan pengacara pelaku?
Klarifikasi polisi soal tiga perkara terpisah terdengar seperti teori konspirasi yang dibuat untuk membersihkan tangan. Fakta sederhananya: dua bersaudara itu kehilangan barang dagangan, menangkap pencuri, menyerahkan ke polisi, lalu ditangkap. Jika itu bukan kriminalisasi, lalu apa namanya?
Hukum harus menjadi tameng, bukan pedang yang menusuk korban. Jika Polrestabes Medan ingin membuktikan profesionalisme, bukan klarifikasi yang dibutuhkan, tapi pembebasan PPS dan LS—berikut permintaan maaf ke publik. Karena jika pembelaan diri dihukum, maka kejahatan telah memenangkan pertandingan sebelum semuanya dimulai.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.