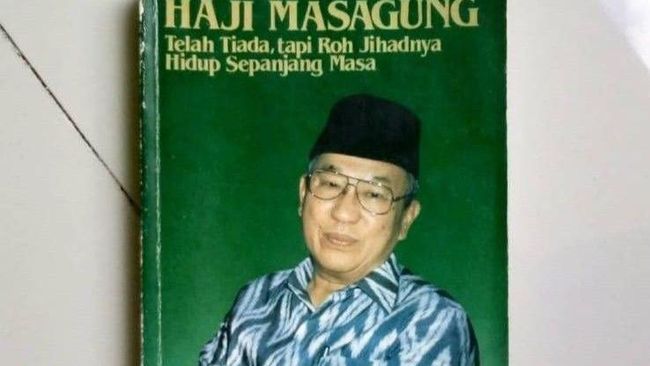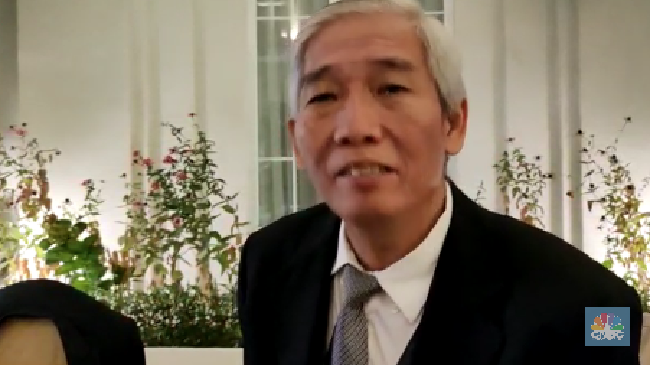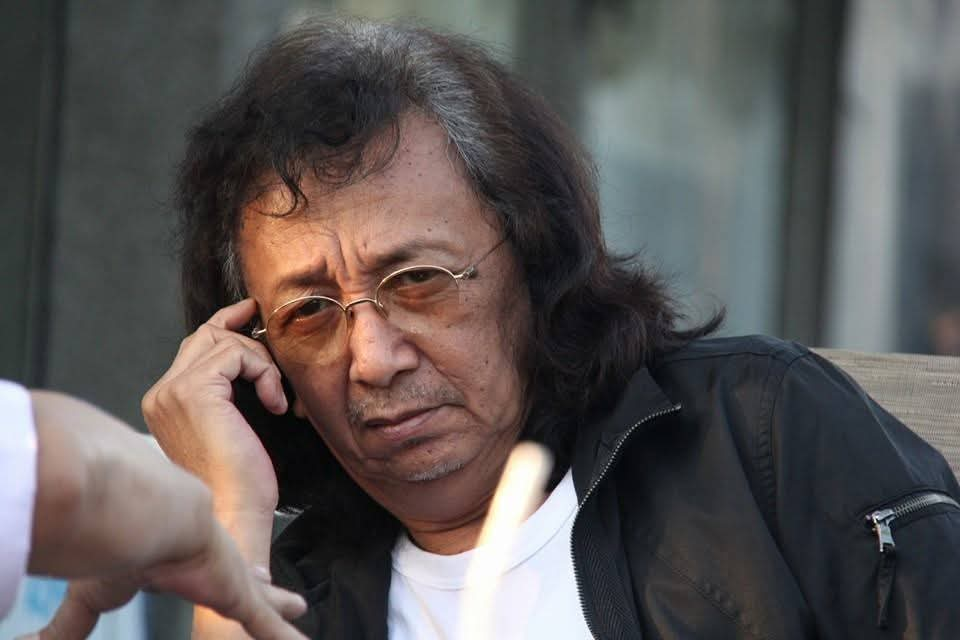Catatan: Artikel ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi CNBCIndonesia.com
Pemerintahan Prabowo-Gibran yang telah berjalan lebih dari satu semester belum menunjukkan sikap pro terhadap ekonomi hijau. Ekonomi hijau yang digaungkan dalam Asta Cita kedua belum mendarat pada tataran aksi dan masih sebatas omon-omon. Realitanya, tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan dan publik tersandera dalam ilusi Astacita.
Jelas ini merupakan ilusi pembohongan publik, sebab, narasi ekonomi hijau yang digaungkan tidak selaras dengan apa yang dikerjakan pemerintah hari ini. Rentetan kebijakan seperti Food Estate, perluasan perkebunan sawit, rencana produksi dimethyl ether (DME), dan tambang nikel Pulau Gag Raja Ampat berpotensi merusak lingkungan. Dampaknya, daerah menjadi korban sebagaimana yang terjadi di Morowali hari ini.
Ilusi Manipulatif
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan ilusi sebagai khayalan; pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan; dan tidak dapat dipercaya. Ya, diksi ilusi tepat disematkan pada implementasi janji ekonomi hijau dalam Asta Cita hari ini. Gagah dalam bicara namun sumbang pada fakta.
Pada aras tata kelola, tidak ada iktikad pemerintah untuk mengubah kebijakan secara ekstrem. Revisi UU 25/2007 tentang Penanaman Modal tidak masuk dalam Daftar Prolegnas 2025-2029, padahal UU ini usang dan konservatif dari segi terminologi maupun konseptual.
Hingga kini, tata kelola investasi hijau di tingkat pusat masih tambal sulam-tanpa dokumen perencanaan khusus, anggaran yang terfragmentasi, kebijakan tanpa arah, dan kelembagaan yang belum jelas. Tidak ada peta jalan nasional yang mengikat, tidak ada kebijakan insentif yang konkret, dan belum ada lembaga khusus yang memimpin orkestrasi investasi hijau lintas sektor.
Pemerintah seolah bicara besar soal transisi hijau, tapi fondasinya rapuh dan belum siap menampung investasi berkelanjutan yang serius. Tidak ada upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan definisi investasi hijau. Bappenas, Kemenperin, KLH, Kementerian Kehutanan, semuanya berjalan masing-masing dengan interpretasi sektoralnya. Akibatnya, implementasi ekonomi hijau rancu dan jalan di tempat.
Pada sisi program, proyek DME yang diklaim sebagai energi bersih justru menghasilkan emisi lima kali lebih besar dari LPG-mencapai 824.000 ton CO₂ per tahun (catatan AEER). Rencana Danantara Indonesia membiayai proyek senilai Rp180 triliun ini jelas keliru dan bertentangan dengan prinsip investasi berkelanjutan, jauh dari praktik Temasek (Singapura) yang mengutamakan portofolio hijau.
Proyek Food Estate dan hilirisasi nikel menunjukkan ilusi pembangunan berkelanjutan. Perusakan hutan dan tindakan represif terhadap masyarakat adat mencerminkan kegagalan memahami prinsip no one left behind.
Pola serupa tampak di Pulau Gag, Raja Ampat, di mana tambang nikel mengabaikan lingkungan dan hak masyarakat lokal. Obsesi alih fungsi lahan untuk bisnis eksploratif-destruktif terus melaju, "tabrak-tabrak masuk", menabrak batas etis dan ekologis pembangunan.
Itu sebabnya dunia tak melirik Konoha (sebutan sinis Indonesia di medsos) sebagai kawasan ideal investasi hijau. Southeast Asia's Green Economy 2024 Report menujukkan bahwa pada 2023, investasi hijau di Indonesia tercatat sebesar Rp 24,4 triliun (sekitar USD 1,594 miliar), hanya sekitar 1,7% dari total realisasi investasi nasional yang mencapai Rp 1.418,9 triliun (Kementerian Investasi, 2023).
Kesenjangan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia kerap menarasikan komitmen ekonomi hijau, kenyataannya masih belum menjadi arus utama dalam strategi ekonomi nasional. Kita belum sepenuhnya merdeka dari kepentingan politis-pragmatis kaum elit yang menghendaki jalan destruktif.
Pertobatan Ekologis
Alasan utama sepinya minat investor untuk mendukung ekonomi hijau di Indonesia adalah hambatan regulatif-struktural di sejumlah aspek seperti dominasi batu bara; regulasi yang tidak kompatibel; minimnya infrastruktur energi terbarukan; dan terbatasnya akses pendanaan hijau. Kurangnya edukasi lembaga keuangan, persepsi risiko tinggi terhadap proyek hijau, serta insentif pemerintah yang belum optimal turut memperburuk keadaan.
Perwujudan ekonomi hijau semestinya berangkat dari kesadaran bahwa mengejar pertumbuhan ekonomi harus selaras dengan komitmen menjaga lingkungan. Raworth (2012) dalam Doughnut Economy mengajarkan kita untuk beralih dari model ekonomi klasik yang mengejar pertumbuhan menjadi fokus pada pemenuhan kebutuhan manusia dan tetap berada dalam batas alami bumi. Maka, berhentilah bicara soal pertumbuhan 8% yang hipokrit dan sekedar terjemahan diksi "Asta" itu sendiri.
Ekonomi restoratif bisa menjadi jalan menuju implementasi ekonomi hijau. Celios (2024) memperkirakan bahwa strategi ini akan mendorong pertumbuhan inklusif-dengan potensi dampak Rp2.208 triliun dalam 25 tahun dan penurunan rasio gini hingga 15%. Cambridge Econometrics turut memperkirakan bahwa setiap Rp. 20.000 yang dikeluarkan untuk penghijauan akan kembali sebesar Rp. 57.000 dalam bentuk benefit ekonomi dan sosial.
Kajian tersebut menunjukkan bahwa pendekatan restoratif adalah solusi ilmiah untuk mengatasi ketimpangan, pertumbuhan, dan krisis ekologis secara simultan. Tentunya, dilakukan secara teknokratik dan melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, hingga dunia usaha secara deliberatif.
Indonesia tentu saja membutuhkan sokongan investor untuk merealisasikan ekonomi hijau. Ekonomi restoratif perlu digaungkan dalam tata kelola investasi pusat hingga daerah, mulai dari perencanaan, kebijakan, kelembagaan, hingga penganggaran. Tentunya diawali dengan political will dan pertobatan ekologis lingkaran istana.
Tidak ada kata terlambat bagi pemerintah untuk melakukan pertobatan ekologis sebagaimana amanat Paus Fransiskus dalam Laudato Si. Pandangan beliau ihwal cinta pada ibu bumi semestinya selaras dengan kita yang kerap mempersonifikasikan Indonesia dengan frasa "ibu pertiwi".
Berhentilah menciptakan ilusi yang menyilaukan simpatisan dan penjilat politik, namun melukai rakyat di pelosok nusantara. Jika pemerintah tidak melakukan perubahan signifikan, maka benarlah kata Itachi Uchiha (tokoh dalam serial Naruto): "pengetahuan dan kesadaran yang tidak jelas, mungkin lebih baik disebut ilusi". Mungkin ekonomi bertumbuh, namun akan melambat dan alam kian rusak akibat ketidaksadaran dalam ilusi yang mereka ciptakan sendiri.
(miq/miq)

 2 months ago
33
2 months ago
33