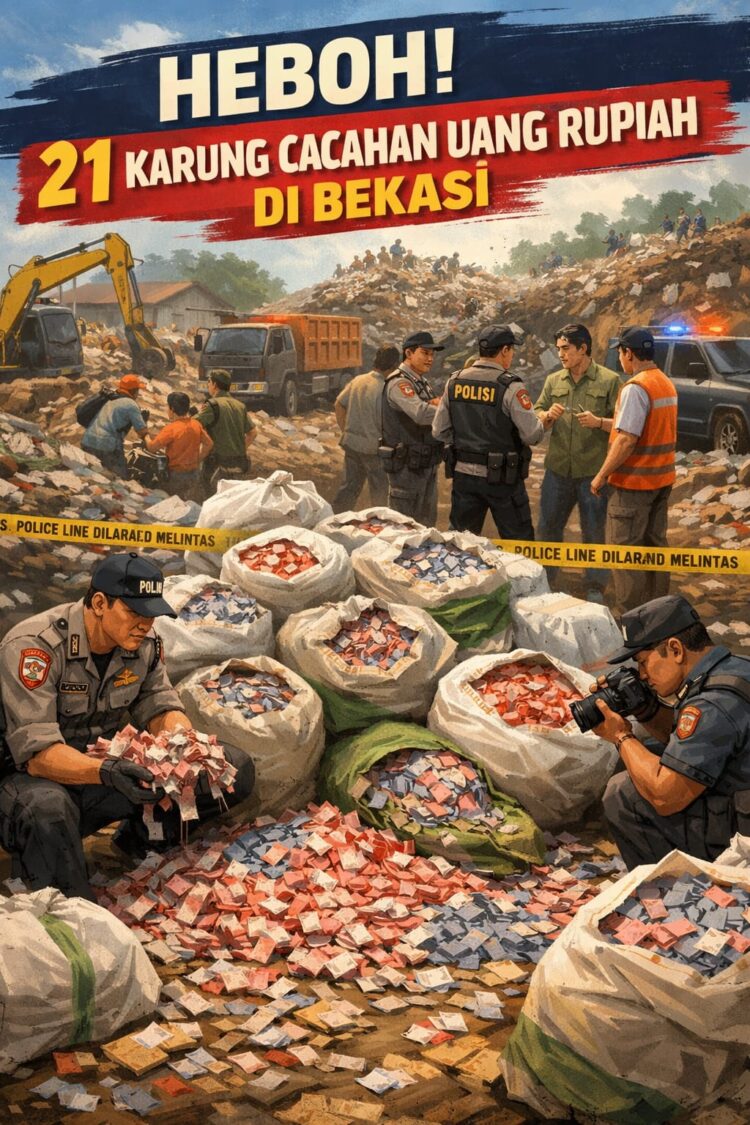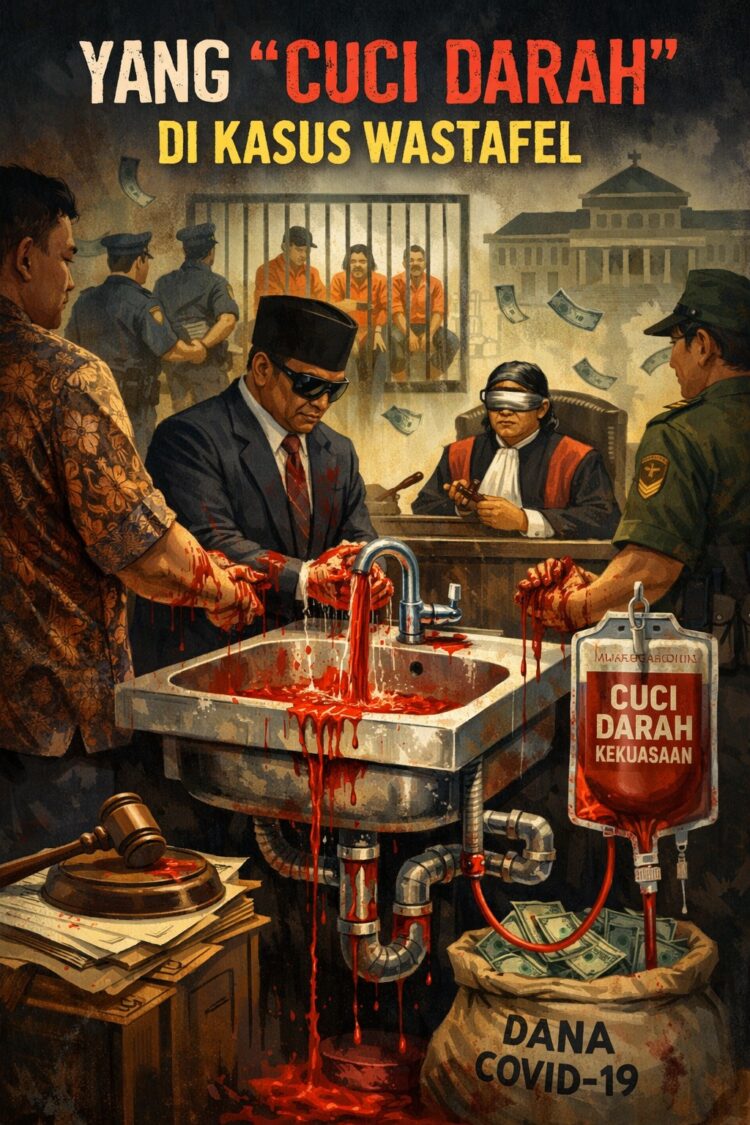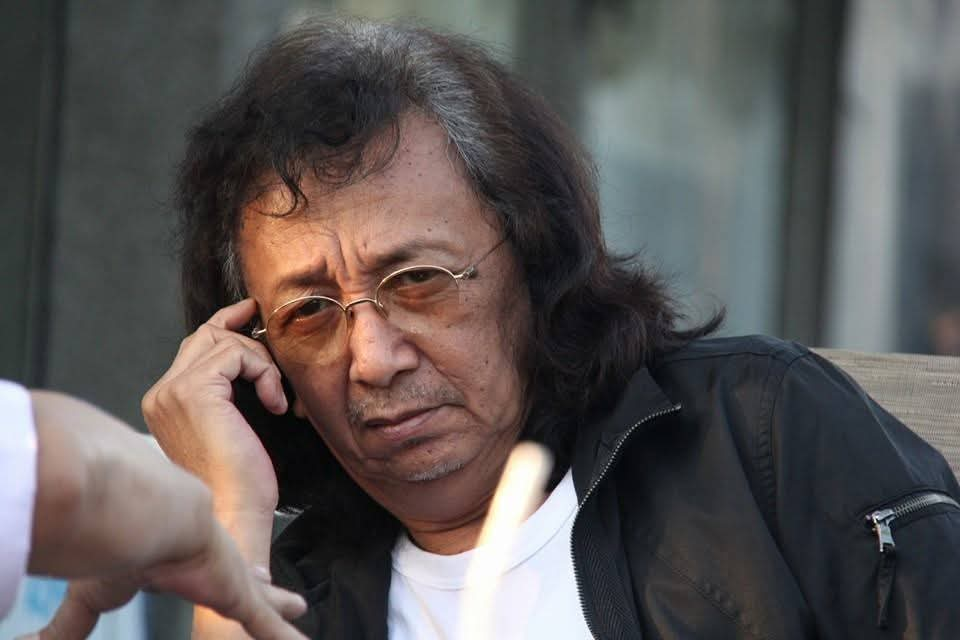Oleh: Ade Jona Prasetyo, S.H., M.H., M.M.
Anggota DPR-RI 2024-2029, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2025.
Pendahuluan
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Dalam negara hukum modern, teori kepastian hukum memegang peranan vital untuk membangun sistem peraturan yang adil, dapat diprediksi, dan tidak diskriminatif. Kepastian hukum sering disebut sebagai salah satu tujuan utama hukum di samping keadilan dan kemanfaatan (Atmadja & Budiartha, 2018). Prinsip ini menuntut agar hukum dirumuskan dengan jelas, konsisten, dan stabil sehingga dapat memberikan perlindungan dan pedoman bagi setiap subjek hukum, baik individu maupun entitas bisnis.
Para pakar menjelaskan bahwa kepastian hukum secara materiil tercermin dari: aturan yang jelas, konsisten, dan mudah diakses, diterbitkan oleh otoritas yang sah; penegak hukum dan instansi pemerintah yang konsisten menerapkan aturan tersebut (serta turut terikat padanya); perilaku masyarakat yang menyesuaikan dengan aturan; peradilan yang independen dan imparsial dalam menegakkan hukum; serta putusan pengadilan yang efektif dilaksanakan (Atmadja & Budiartha, 2018). Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, hukum mampu berfungsi sebagai instrumen pemenuhan rasa keadilan dan keamanan bagi masyarakat.
Tantangan muncul dalam praktik ketatanegaraan Indonesia belakangan ini. Era deregulasi termasuk penerapan metode omnibus law seperti UU Cipta Kerja yang bertujuan menyederhanakan aturan, justru diiringi gejala ambiguitas norma dan disharmonisasi peraturan. Sering ditemukan pertentangan atau tumpang-tindih antara peraturan secara vertikal (misalnya antara undang-undang dengan peraturan pemerintah) maupun horizontal (antar sektor atau kementerian).
Alih-alih menyatukan regulasi, penerapan omnibus law tanpa perencanaan matang memicu ketidakjelasan hierarki aturan dan multitafsir kewenangan. Contohnya, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 91/PUU- XVIII/2020 tentang UU Cipta Kerja memberikan status “inkonstitusional bersyarat” alih-alih membatalkan langsung undang-undang tersebut. Keputusan MK yang bersayap ini dianggap “setengah hati” dan memunculkan ketidakpastian baru di masyarakat (Robbi, 2021).
Dalam amar putusannya, MK menangguhkan berbagai kebijakan strategis terkait UU Cipta Kerja tanpa memberi ukuran jelas tentang apa yang dimaksud “strategis dan berdampak luas”. Akibatnya, pemerintah dapat menafsirkan sendiri ruang lingkup penangguhan, sehingga beberapa ketentuan UU Cipta Kerja tetap dijalankan sementara yang lain tertunda. Larangan menerbitkan peraturan pelaksana baru selama dua tahun juga membuat sejumlah norma tidak dapat diimplementasikan, meski substansinya sudah diatur di tingkat undang-undang (Robbi, 2021).
Substansi putusan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum yang luas, karena aturan ada tetapi mandul tanpa petunjuk pelaksana. Situasi ini menunjukkan bahwa regulasi hasil deregulasi yang tidak cermat perumusannya justru dapat mengganggu kepastian hukum dan merugikan kepentingan publik maupun dunia usaha.
Teori Kepastian Hukum dalam Perspektif Kelsen, Radbruch, dan Savigny
Untuk menganalisis persoalan di atas, teori kepastian hukum dari para pemikir klasik dapat dijadikan pisau bedah yang berguna. Hans Kelsen, melalui teori hukum murni-nya, menekankan pentingnya legalitas dan tata urutan norma dalam sistem hukum. Hukum dipandang sebagai hierarki norma (Stufenbau) yang tersusun rapi; norma dasar (grundnorm) menjadi puncak yang memberi validitas bagi norma di bawahnya.
Kelsen berpendapat bahwa hukum harus dipisahkan dari unsur sosial atau moral (pemisahan das Sein dan das Sollen), sehingga kajian hukum bersifat normatif murni. Menurut Kelsen, undang-undang yang memuat aturan umum berfungsi sebagai pedoman tingkah laku bagi masyarakat, dan pelaksanaan aturan secara konsisten akan menimbulkan kepastian hukum (Gunardi, 2022, p. 9). Kelsen mengaitkan kepastian hukum dengan prinsip imputasi, artinya suatu perbuatan yang melanggar norma harus dihubungkan dengan sanksi yang ditetapkan oleh norma tersebut (p. 9).
Dengan adanya sanksi tegas, setiap orang dapat meramalkan konsekuensi hukum dari tindakannya, sehingga tercipta prediktabilitas dalam interaksi sosial. Hierarki norma yang terstruktur dan penegakan hukum berdasarkan aturan tertulis inilah yang memberi kepastian (legal certainty), sekaligus membedakan hukum dari sekadar anjuran moral.
Di lain pihak, Gustav Radbruch menawarkan perspektif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan nilai keadilan. Filsuf hukum asal Jerman ini dikenal dengan konsep “triadik tujuan hukum”, yaitu: keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Radbruch mengakui pentingnya kepastian demi order dan ketertiban, namun ia menegaskan titik berat ide hukum seharusnya adalah nilai keadilan berupa jaminan dan perlindungan atas kesetaraan (Moeliono & Sebastian, 2015).
Menurut Radbruchsche Formel yang termasyhur, bila suatu aturan positif dalam penerapannya sedemikian rupa bertentangan dengan rasa keadilan hingga pada tahap intolerable injustice, maka hakim berhak mengesampingkan kepastian hukum demi tegaknya keadilan substantif. Pandangan ini muncul dari pengalaman rezim tirani, ketika hukum tertulis dijalankan secara pasti namun mengabaikan moralitas (contoh ekstrem: hukum rasis era Nazi yang formalnya sah tetapi sangat tidak adil). Radbruch mengingatkan bahwa kepastian hukum yang kaku tanpa koreksi etis dapat menjelma ketidakadilan. Oleh karenanya, hukum harus “luwes” dikoreksi oleh tuntutan keadilan agar tujuan hukum sebagai pengayom hak asasi dan martabat manusia tercapai.
Sementara itu, Friedrich Carl von Savigny (tokoh Mazhab Sejarah) menyoroti pentingnya konteks sosiokultural dalam penciptaan kepastian hukum. Savigny berpendapat hukum adalah manifestasi dari jiwa atau kepribadian suatu bangsa (Volksgeist) (Atmadja & Budiartha, 2018). Ada hubungan organik antara hukum dan karakter masyarakat; hukum yang hidup secara alamiah dalam adat-istiadat itulah hukum sejati, sedangkan legislasi (undang-undang tertulis) idealnya hanya bersifat deklaratif atau merumuskan apa yang sudah hidup sebagai law in action. Implikasinya, perubahan atau pembaruan hukum tidak bisa dilakukan secara dadakan hanya karena alasan pragmatis, melainkan harus memperhatikan tradisi dan kebutuhan nyata masyarakat.
Kepastian hukum menurut Savigny bukan sekadar kepastian teks normatif, tapi kepastian bahwa hukum tersebut berakar pada nilai-nilai sosial yang diakui bersama. Dalam konteks Indonesia yang majemuk, pemikiran Savigny relevan sebagai peringatan agar deregulasi atau modernisasi hukum tidak memutus kesinambungan dengan living law (hukum adat dan praktik lokal). Jika hukum nasional terlalu mengabaikan Volkgeist lokal, maka aturan baru berisiko tidak efektif atau ditolak komunitas, sehingga justru menggerus kepastian hukum secara empiris.
Ketiga perspektif di atas, memberikan landasan teoretis yang saling melengkapi dalam memahami kepastian hukum. Kelsen menekankan kepastian dari sisi struktur formal dan konsistensi logis sistem norma; Radbruch menekankan dimensi etis bahwa kepastian harus diarahkan menuju keadilan; dan Savigny mengingatkan dimensi historis-sosiologis bahwa kepastian juga bertumpu pada penerimaan sosial.
Dengan menggabungkan ketiganya, kita mendapat pemahaman utuh bahwa kepastian hukum bukan sekadar kepastian bunyi undang-undang, tetapi mencakup kepastian secara moral (adil) dan sosiologis (diakui masyarakat). Inilah yang seharusnya menjadi acuan dalam pembentukan maupun pelaksanaan hukum di era deregulasi yang sarat perubahan cepat.
Ambiguitas Regulasi dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum
Realitas pasca berbagai paket deregulasi menunjukkan gap antara teori dan praktik. Pemerintah, dalam upaya memangkas aturan yang dianggap menghambat investasi, bergerak cepat mengesahkan regulasi baru (seperti UU No. 11/2020 Cipta Kerja dan peraturan turunannya). Sayangnya, kecepatan ini sering tidak diimbangi dengan kajian mendalam atas asas legalitas, kejelasan perumusan, maupun partisipasi publik.
Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai UU No. 12 Tahun 2011, seperti keterbukaan dan clarity of norms, seringnya terabaikan. Akibatnya, muncul peraturan yang inkonsisten atau multitafsir. Sebagai ilustrasi, pasca diundangkannya UU Cipta Kerja, ditemukan sejumlah kesalahan rujukan pasal dan tumpang-tindih pengaturan, hingga pemerintah terpaksa menerbitkan errata (perbaikan naskah) yang ironisnya menambah perdebatan mengenai legitimasi proses legislasi. Di tingkat teknis, banyak peraturan pelaksana (Peraturan Pemerintah, Perpres, dll.) yang terbit tergesa-gesa sehingga tidak selaras satu sama lain.
Hal ini mengakibatkan disharmonisasi: misalnya ketidaksesuaian antara peraturan sektor lingkungan hidup dan aturan sektor investasi, atau benturan kewenangan pusat-daerah dalam penerapan perizinan terpadu. Ambiguitas dan disharmoni regulasi semacam ini merusak kepastian hukum, karena pelaksana dan masyarakat kebingungan mana ketentuan yang harus diikuti. Bagi dunia usaha, ketidakpastian regulasi jelas berpengaruh negatif terhadap iklim investasi, investor enggan menanam modal jika aturan main mudah berubah atau tidak jelas.
Selain itu, produk deregulasi yang cacat formil membuka pintu lebar bagi gugatan hukum. Mahkamah Konstitusi telah menjadi arena “pengujian” bagi banyak UU hasil omnibus law. Putusan MK terkait UU Cipta Kerja pada 2021 merupakan contoh nyata: MK menyatakan UU tersebut inkonstitusional bersyarat karena prosedur pembentukannya menyimpang asas (terutama minimnya partisipasi publik).
Putusan MK itu mengandung pesan tegas bahwa pembentuk undang-undang (Presiden dan DPR) wajib mematuhi standar formil dan materiil dalam pembuatan regulasi (Robbi, 2021). Jika tidak, hasil deregulasi justru rentan dibatalkan dan membawa implikasi ketidakpastian lebih besar. Faktanya, pemerintah akhirnya harus menerbitkan Perpu No. 2 Tahun 2022 untuk “menyelamatkan” UU Cipta Kerja, yang kemudian disahkan menjadi UU No. 6 Tahun 2023 yang merupakan langkah yang menuai pro-kontra dan gugatan lanjutan.
Semua ini menunjukkan bahwa politik hukum pragmatis yang semata mengejar kemudahan investasi, bila mengabaikan rule of law dan asas-asas kepastian, akan berujung kontraproduktif. Regulasi yang tidak koheren dan tidak legitimate justru melahirkan ketidakpastian baru, bertentangan dengan tujuan awal deregulasi itu sendiri.
Dari sini, teori kepastian hukum menuntut agar pembuat kebijakan tidak hanya berpikir jangka pendek, tetapi merancang aturan secara cermat dan komprehensif. Setiap omnibus law atau paket deregulasi harus diuji keselarasan vertikalnya (dengan konstitusi dan UU lain) dan horizontalnya (antar sektor). Teori Hans Kelsen mengingatkan pentingnya hirarki norma, misalnya, dalam membuat UU Cipta Kerja yang mengubah puluhan UU lain, semestinya dijaga konsistensi sehingga tidak ada aturan turunan yang bertentangan dengan UU induk. Begitu pula, asas legalitas menghendaki rumusan norma tidak boleh sumir atau ambigu.
Jika dalam satu UU banyak pendelegasian aturan ke PP/Perpres tanpa standar yang jelas, peluang interpretasi berbeda-beda akan tinggi sehingga kepastian hukum melemah. Di sinilah peran lembaga pengawasan legislasi harus dioptimalkan. Badan Legislasi DPR RI bersama Kementerian/Lembaga terkait seyogianya melakukan harmonisasi sejak tahap perancangan undang-undang.
Pasca diundangkan, Mahkamah Agung dapat menguji peraturan di bawah UU agar tidak terjadi pertentangan vertikal. Sedangkan Mahkamah Konstitusi berperan sebagai penjaga konstitusionalitas dan nilai-nilai keadilan dalam UU. Supaya tidak setiap kebijakan strategis dibatalkan MK, pembuat UU harus bercermin pada putusan-putusan MK sebelumnya, memastikan prosedur dan materi aturan tidak melanggar UUD 1945 maupun asas pembentukan yang baik. Dengan kolaborasi checks-and-balances seperti itu, integritas sistem hukum dapat terjaga dan arus deregulasi dapat diarahkan tetap sejalan dengan prinsip negara hukum.
Integrasi Pendekatan Sosiologis: Pluralisme Hukum dan Hukum Responsif
Teori kepastian hukum tidak boleh dimaknai secara sempit (formalistik) semata, melainkan harus dilihat dalam konteks sosial tempat hukum berlaku. Dalam masyarakat plural seperti Indonesia, hukum negara berinteraksi dengan hukum adat dan norma agama yang hidup di komunitas lokal. Konsep pluralisme hukum menjadi relevan: di satu negara dapat berlaku banyak sistem hukum sekaligus, baik formal maupun non-formal.
John Griffiths mendefinisikan pluralisme hukum sebagai keberadaan lebih dari satu aturan hukum dalam suatu lingkup sosial, di mana konsep ini menolak dikotomi kaku antara “hukum negara” versus “hukum rakyat/agama” (Flambonita, 2021). Artinya, living law dalam masyarakat (misal: hukum adat, praktek komunitas) seyogianya diakomodasi atau setidaknya dipertimbangkan oleh pembentuk kebijakan. Dengan mengakui pluralitas sumber hukum, kepastian hukum secara substantif justru dapat ditingkatkan – sebab aturan formal akan selaras dengan rasa keadilan lokal dan tidak mudah menimbulkan konflik sosial.
Sebaliknya, jika deregulasi hanya berfokus pada unifikasi aturan demi efisiensi (one size fits all) tanpa sensitivitas kearifan lokal, hasilnya bisa jadi kepastian semu di atas kertas, tapi chaos di lapangan. Maka, pendekatan sosiologis mengingatkan kita bahwa kepastian tidak sama dengan kekakuan; ia harus lentur merangkul keragaman, agar hukum benar-benar pasti ditegakkan karena didukung penerimaan masyarakat.
Selain pluralisme hukum, teori hukum modern mengenal konsep hukum responsif (responsive law) yang diperkenalkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick. Hukum responsif merupakan reaksi terhadap kelemahan hukum otonom yang terlalu formalistis. Dalam paradigma hukum otonom (liberal legalism), hukum dianggap institusi mandiri dengan aturan dan prosedur objektif yang netral, terpisah dari politik atau kepentingan masyarakat[12].
Model ini menjunjung tinggi rule of law namun cenderung melihat hukum sebagai tujuan itu sendiri. Kritik dari Nonet & Selznick menunjukkan bahwa ketika hukum diisolasi dari realitas sosial, ia justru bisa berubah menjadi institusi yang melayani dirinya sendiri, bukannya melayani manusia (Sulaiman, 2015). Hukum yang terlalu kaku dan tertutup berpotensi mandul sebagai sarana perubahan dan gagal mencapai keadilan substantif.
Sebagai solusinya, hukum responsif menawarkan orientasi hukum yang peka terhadap kebutuhan sosial dan tanggap terhadap aspirasi masyarakat. Ciri utama hukum responsif antara lain pergeseran penekanan dari aturan-aturan teknis ke prinsip-prinsip dan tujuan hukum yang lebih luas, serta pentingnya partisipasi dan watak kerakyatan baik sebagai tujuan maupun dalam proses pembentukan hukum (Sulaiman, 2015).
Dengan kata lain, hukum harus mau mendengar suara rakyat (bottom-up) dan bersedia menyesuaikan diri dengan perubahan kondisi sosial ekonomi. Nonet & Selznick menyatakan bahwa pencarian bentuk hukum yang lebih responsif ini telah menjadi perhatian besar teori hukum modern, demi menjadikan hukum lebih efektif mengabdi kepentingan publik dan nilai-nilai demokratis (Sulaiman, 2015).
Penerapan konsep hukum responsif dalam konteks kepastian hukum berarti mengharmonikan aturan dengan realitas. Kepastian hukum bukan berarti aturan tidak boleh diubah – justru aturan harus dinamis merespons perkembangan zaman, namun perubahan itu harus terprediksi dan terkelola. Misalnya, pemerintah dalam deregulasi seharusnya melibatkan dialog publik dan pakar sejak awal, sehingga aturan yang dihasilkan responsif menjawab masalah tanpa menimbulkan ketidakpastian baru. Asas transparansi dan partisipasi di sini berperan: proses legislasi yang terbuka memungkinkan tercapainya konsensus atau setidaknya pemahaman bersama, sehingga ketika aturan baru diberlakukan, masyarakat telah siap menyesuaikan diri.
Ini sejalan dengan pandangan hukum responsif di mana legitimasi hukum diperoleh dari dukungan sosial. Hukum yang responsif juga mendorong penegakannya secara fleksibel sesuai konteks, tanpa mengorbankan konsistensi. Sebagai contoh, dalam menerapkan regulasi investasi, pemerintah perlu tetap responsif terhadap kekhawatiran lingkungan dan komunitas lokal – artinya ada mekanisme evaluasi dan revisi aturan bila terbukti menimbulkan efek negatif.
Pendekatan semacam ini akan menjaga kepastian hukum jangka panjang, karena hukum membangun kredibilitas sebagai institusi yang rasional sekaligus berperikemanusiaan. Masyarakat dan pelaku usaha akan lebih percaya pada hukum yang pasti tapi lentur dibanding hukum yang pasti tapi membuta.
Penutup
Dapat disimpulkan bahwa penegakan teori kepastian hukum merupakan fondasi dalam menyikapi ambiguitas regulasi di era deregulasi. Kepastian hukum bukanlah tujuan legalistik semata, melainkan prinsip normatif yang menjamin rasionalitas dan keadilan sistem hukum.
Dengan berpegang pada teori ini, pemerintah dan legislatif diingatkan untuk tidak terjebak pada euforia deregulasi yang mengabaikan asas-asas fundamental negara hukum. Justru di tengah arus perubahan regulasi yang cepat, prinsip kepastian hukum menjadi jangkar agar kapal legislasi tidak oleng menghantam karang ketidakpastian.
Upaya membangun sistem hukum nasional yang inklusif, adil, dan tangguh harus dimulai dari regulasi yang jelas dan harmonis. Tentu, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan kemanfaatan dan keadilan – ketiganya adalah pilar yang saling menguatkan. Rule of law yang pasti tetapi tidak adil akan kehilangan legitimasi, sebaliknya hukum yang adil namun tidak pasti penegakannya akan gagal memberi perlindungan.
Oleh karena itu, dalam setiap agenda deregulasi dan reformasi hukum, teori kepastian hukum menyediakan kerangka evaluatif untuk menakar apakah perubahan regulasi yang diusulkan telah memenuhi syarat kejelasan dan konsistensi, tanpa mengorbankan keadilan substansial bagi rakyat.
Melalui integrasi wawasan teoritis (dari Kelsen, Radbruch, Savigny) dan pendekatan modern (pluralisme hukum, hukum responsif), diharapkan lahir kebijakan hukum yang pro-investasi sekaligus pro-pemerintahan yang tertib dan pro-masyarakat. Dengan demikian, kepastian hukum berfungsi sebagai penjaga keseimbangan: menjamin iklim usaha dan pembangunan dapat bergerak maju, namun tetap dalam koridor konstitusi, penghormatan hak asasi, dan nilai-nilai lokal yang dijunjung. Inilah kunci agar deregulasi tidak berubah menjadi deregulasi liar, melainkan transformasi hukum yang berkesinambungan dan kokoh di atas prinsip negara hukum.
- Biography Penulis
Ade Jona Prasetyo adalah adalah seorang politisi dan praktisi hukum yang menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2024–2029 dari Fraksi Partai Gerindra, serta menjabat sebagai Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Utara. Di samping kiprah politiknya, ia aktif dalam berbagai organisasi, termasuk Ketua Bidang Hilirisasi Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan Ketua organisasi olahraga serta komunitas sosial di tingkat daerah. Secara akademik, Ade Jona menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (S.H.) dan dua gelar Magister, yakni Magister Hukum (M.H.) dan Magister Manajemen (M.M.). Saat ini, sedang menyelesaikan studi doktornya pada Program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia.
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.