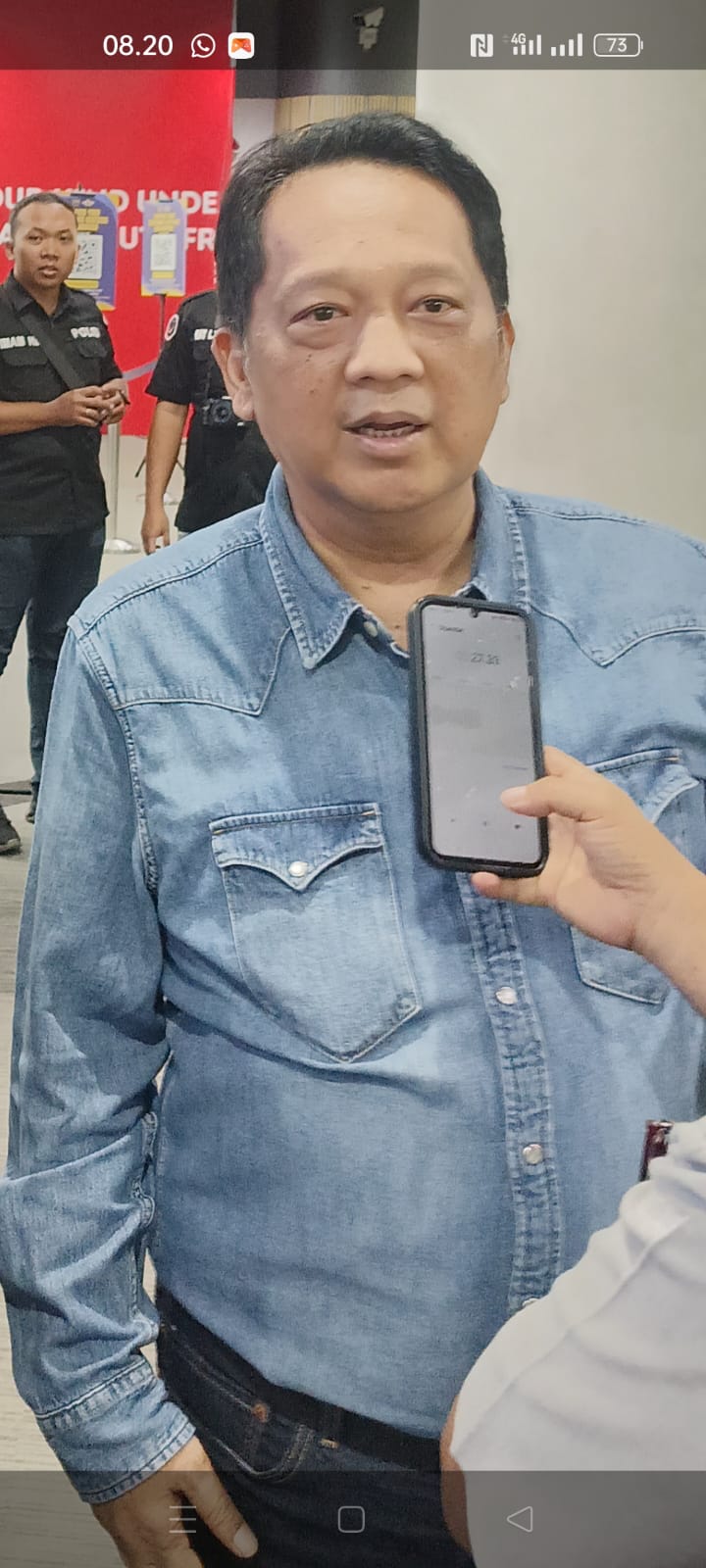Oleh: Farid Wajdi
Bencana selalu datang tanpa undangan. Ia merobohkan rumah, merendam ingatan, dan memaksa manusia berhadapan langsung dengan batas paling rapuh dari peradabannya.
Scroll Untuk Lanjut Membaca

IKLAN
Namun di negeri ini, setiap kali bencana tiba, ia kerap diikuti rombongan lain yang justru datang dengan undangan: rombongan kekuasaan. Kamera menyala, sepatu lapangan masih mengilap, dan kalimat empati dihafal dengan rapi. Inilah yang oleh publik disebut dengan getir sebagai wisata bencana.
Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegur praktik ini. “Jangan wisata bencana,” ujarnya, sebagaimana diberitakan Detik.com (2025), Metro TV (2025), Kompas.com (2025), dan CNN Indonesia (2025).
Teguran itu bukan sekadar larangan etik, melainkan kritik keras terhadap cara kekuasaan memaknai kehadiran. Bencana, dalam pandangan Presiden, bukan panggung. Ia adalah ruang kerja darurat yang menuntut efektivitas, bukan eksistensi.
Wisata bencana adalah ironi kekuasaan. Ia lahir ketika penderitaan rakyat berubah menjadi latar visual, ketika duka dijadikan dekorasi, dan ketika kehadiran pejabat lebih sibuk membuktikan “saya sudah datang” daripada “apa yang sudah saya putuskan”.
Dalam logika ini, kamera lebih penting daripada koordinasi, dan unggahan media sosial lebih cepat daripada distribusi logistik.
Video-video yang beredar di YouTube (2025) memperlihatkan paradoks itu secara telanjang: relawan berhenti bekerja karena iring-iringan pejabat melintas, aparat sibuk mengatur barikade protokoler, sementara korban berdiri menunggu bukan bantuan, tetapi selesainya sesi foto. Di titik inilah negara kehilangan kepekaannya, bukan karena tidak hadir, tetapi karena hadir dengan cara yang keliru.
Masalah utama wisata bencana bukanlah kehadiran fisik pejabat. Kehadiran bisa penting, bahkan diperlukan. Masalahnya adalah ketiadaan nilai tambah. Ketika kunjungan tidak mempercepat pengambilan keputusan, tidak membuka akses anggaran, tidak memotong rantai birokrasi, dan tidak memperjelas komando lapangan, maka kehadiran itu bukan hanya sia-sia—ia kontraproduktif.
Presiden Prabowo menyebut secara spesifik Sumatra agar tidak dijadikan “wisata bencana” (MetroTVNews, 2025). Pernyataan ini penting karena ia mengakui satu kenyataan pahit: bahwa di tengah darurat, terlalu banyak energi negara habis untuk melayani simbol, bukan substansi. Negara yang sibuk menyambut pejabat justru lupa menyelamatkan warga.
Fetisisme Kehadiran
Wisata bencana juga mencerminkan penyakit lama birokrasi: fetisisme kehadiran. Dalam budaya administratif kita, pejabat merasa belum bekerja jika belum “turun ke lapangan”, meskipun tanpa mandat jelas.
Padahal, dalam manajemen bencana modern, yang paling dibutuhkan bukanlah jumlah pejabat di lokasi, melainkan ketepatan komando. Terlalu banyak aktor tanpa peran jelas hanya melahirkan kebisingan.
Sindiran Presiden terhadap pejabat yang “foto-foto di tengah banjir” (Kompas.com, 2025) adalah tamparan simbolik. Kamera, dalam konteks ini, bukan sekadar alat dokumentasi, tetapi simbol relasi kuasa. Ia menempatkan korban sebagai objek visual, bukan subjek yang harus dilayani. Dalam satu klik, penderitaan direduksi menjadi konten.
Lebih jauh, wisata bencana berpotensi menjadi bentuk kekerasan simbolik. Ia tidak melukai tubuh, tetapi melukai martabat. Korban dipaksa menampilkan duka di hadapan lensa, sementara pejabat menampilkan empati yang sering kali berakhir di caption media sosial. Di sini, bencana tidak lagi murni tragedi kemanusiaan, melainkan komoditas citra.
Peringatan Presiden Prabowo agar siapa pun tidak datang ke daerah bencana hanya untuk berfoto (CNN Indonesia, 2025) sejatinya adalah upaya mengembalikan etika kekuasaan.
Kekuasaan, dalam situasi darurat, seharusnya bekerja dalam senyap. Keputusan yang tepat waktu lebih berharga daripada pidato panjang. Instruksi yang jelas lebih bermakna daripada pelukan simbolik.
Namun, kritik ini tidak boleh berhenti pada individu. Wisata bencana adalah produk sistemik. Ia tumbuh dalam sistem politik yang mengukur kinerja dari visibilitas, bukan dampak; dari dokumentasi, bukan hasil. Selama laporan kerja lebih menghargai foto kunjungan daripada angka bantuan tersalurkan, praktik ini akan terus berulang.
Empati Yang Bekerja
Di sinilah publik harus bersikap tegas. Kritik terhadap wisata bencana bukan berarti menolak empati pejabat, melainkan menuntut empati yang bekerja. Pejabat boleh datang, tetapi harus membawa keputusan. Bila tidak, bekerja dari jauh dengan instruksi yang efektif jauh lebih bermoral daripada hadir tanpa fungsi.
Bencana sejatinya adalah ujian paling jujur bagi negara. Ia membongkar mana kekuasaan yang bekerja dan mana yang sekadar tampil. Ia memisahkan pejabat yang memahami penderitaan sebagai tanggung jawab dari mereka yang memahaminya sebagai peluang eksposur.
Pada akhirnya, wisata bencana adalah cermin. Ia memantulkan wajah kekuasaan yang lupa merendah di hadapan duka. Teguran Presiden Prabowo seperti yang diberitakan luas oleh Detik.com (2025) dan media nasional lainnya, harus dibaca sebagai ajakan korektif: hentikan politik kunjungan, mulai politik keputusan.
Sebab bagi korban, satu truk logistik yang tiba tepat waktu lebih bermakna daripada sepuluh pejabat yang datang bersamaan. Bagi negara, menghentikan wisata bencana bukan hanya soal efisiensi penanganan, tetapi soal mengembalikan kemanusiaan ke jantung kekuasaan.
Di hadapan bencana, negara tidak butuh penonton. Negara butuh pekerja. Kekuasaan, jika masih ingin bermartabat, harus berani turun bukan untuk dilihat, melainkan untuk menyelesaikan.
Penulis adalah Founder Ethics of Care, Anggota Komisi Yudisial 2015-2020, dan Dosen UMSU
Update berita terkini dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran favoritmu akses berita Waspada.id WhatsApp Channel dan Google News Pastikan Kamu sudah install aplikasi WhatsApp dan Google News.